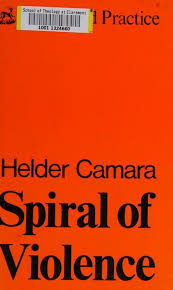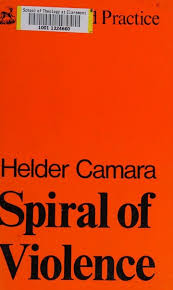1730. Semakin Cerdas Dengan ...
31-07-2025
Klik:
https://www.youtube.com/watch?v=4T5gm7ehGvA
Terutama mulai menit 22 dan seterusnya
Dan jangan berhenti, lihat mulai menit 55 dan seterusnya
1731. Agustus!
02-08-2025
Ada apa dengan Agustus? Ada banyak hal, seperti bulan-bulan lainnya. Tetapi bagi republik, ada hal khusus di Agustus, peringatan kemerdekaan republik. Kemerdekaan bagi banyak komunitas tidak hanya soal kegembiraan menjadi merdeka, bukan hanya soal kebanggaan menjadi bangsa merdeka, tetapi juga adalah soal bagaimana proses menuju-menjadi merdeka itu. Perjuangan dan pengorbanan dari para pendahulu. Juga sebenarnya adalah, bagaimana masa depan akan dihadapi dengan modal besar kemerdekaan itu. Maka dalam peringatan kemerdekaan, tentu ada kegembiraan, tetapi juga sekaligus ada nuansa, katakanlah di republik, sepuluh November, Hari Pahlawan. Ada juga tekad bersama untuk mengisi kemerdekaan dengan lebih baik ke depannya. Maka dalam Upacara Peringatan Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti, ada tiga hal di atas yang perlu diperhatikan. Tujuh belas Agustus nanti bukan hanya soal bernegara, tetapi -meminjam istilah Driyarkara: bagian dari menegara. Sebuah gerak sejarah yang tidak pernah melupakan siapapun yang hadir dalam komunitas. Baik dari segi waktu dalam nuansa masa lalu, sekarang, dan ke depannya, atau semua pihak yang ada dalam republik. Bahkan pihak alam semestanya.
Konsep negara modern adalah sekularisasi dari konsep teologi, demikian menurut Carl Schmitt kira-kira se-abad lalu. Mungkin kita bisa setuju atau tidak, tetapi jika yang dikatakan Carl Schmitt itu tidak salah-salah amat maka bisa dibayangkan memang ada hal-hal tertentu yang ‘sakral’ sifatnya. Atau apapun mau disebut, ada hal-hal yang dijunjung tinggi dalam konsep negara-bangsa. Peringatan hari kemerdekaan seperti digambarkan di atas, bisa pula dibayangkan sebagai salah satu ‘hari raya penting’ yang rutin diperingati dalam konsep teologi. Maka mestinya ada rasa khidmat dalam peringatannya. Tidak hanya kegembiraan dan kebanggaan dalam peringatan kemerdekaan, tetapi juga ke-khidmatan dalam mengenang pendahulu. Apalagi dikibarkan pula ‘bendera pusaka’-nya. Kita tidak usah merasa ragu terkait perlunya segala ke-khidmatan ini, apalagi peristiwa ‘paling khidmat’ ini toh hanya sekali dalam setahun.
Tulisan ini didorong oleh menyusupnya rasa aneh dalam upacara peringatan kemerdekaan bertahun terakhir, yang mana di tempat yang sama dengan upacara itu digelar, terus para menteri jogetan tidak karu-karuan, dan presiden angguk-angguk pelan sambil pecingas-pecingis kecil bak seorang raja besar. Aneh rasanya ketika ada ibadah berlangsung khidmat karena penting dan hanya setahun sekali itu misalnya, di tempat ibadah yang sama itu kemudian dilanjutkan dengan joget-joget tidak karu-karuan. Apakah kegembiraan tidak boleh dengan jogetan? Tentu boleh. Masalahnya, apa iya tidak ada tempat lain selain jogetan di tempat upacara (sakral) itu?
Arnold J. Toynbee dalam ‘psikologi pertemuan budaya’ mengatakan bahwa sinar budaya yang nilainya ‘rendah’ akan lebih mudah ‘masuk’ dibandingkan dengan yang nilainya ‘tinggi’. Ke-khidmatan upacara yang dibangun selama, katakanlah satu-dua jam, bisa-bisa menguap begitu saja ketika di tempat yang sama para menteri pethakilan joget tidak karu-karuan. Seperti di beberapa tahun terakhir. Bolehkah untuk menampakkan kegembiraan dengan jogetan? Tentu boleh. Mau komplit dengan koprol atau kayangpun boleh, tetapi sebaiknya jangan di tempat yang sama ketika kekhidmatan itu terbangun.
Menurut Hannah Arendt, selain ada vita activa (kerja, karya, tindakan) ada juga vita contemplativa. Jogetan di tempat dimana ke-khidmatan upacara peringatan kemerdekaan baru saja terbangun, dan itulah yang dilakukan rejim kerja-kerja-kerja bertahun terakhir, tidak hanya menggeser vita contemplativa yang bahkan hanya satu hari dalam satu tahun itu, tetapi juga mengolok-oloknya. Habis-habisan. Rejim yang tahunya hanya ‘kerja’, jauh dari ‘karya’, jauh dari ‘tindakan’. Bahkan vita contemplativa-pun diolok-oloknya. Tanpa beban. *** (02-08-2025)
1732. One Piece vs AbD
04-08-2025
Yang dimaksud dengan AbD dalam judul adalah accumulation by dispossession, diperkenalkan oleh David Harvey di sekitar awal-awal abad 21. Sepuluh tahun setelahnya, Thomas Piketty menerbitkan bukunya Capital in the Twenty-First Century (2013) yang salah satunya menggambarkan bagaimana ketimpangan sungguh sudah sangat memprihatinkan. Bagaimana setengah populasi dunia (50%) hanya menguasai 2% kekayaan global saja. Sedangkan 10% populasi bisa-bisanya menguasai 76% kekayaan. Dari ‘anggota’ yang 10% itu, katakanlah 1% populasi, mereka menguasai 38% kekayaan!
Dispossession sendiri sering diterjemahkan sebagai pengusiran, perampasan. Rampok, katakanlah begitu. Jadi accumulation by dispossession (AbD) adalah akumulasi (kekayaan) melalui jalan pengusiran, perampasan. Melalui jalan merampok. David Harvey menggambarkan AbD sebagai pengembangan apa dari yang disebut Marx sebagai akumulasi primitif. AbD menurut Harvey adalah modus utama ((akumulasi) dalam kapitalisme neoliberal. Apa itu neoliberalisme? Menurut Pierre Bourdieu, esensi neoliberalisme adalah a programme for destroying collective structures which may impede pure market logic’ (1998).[1] Sebagai konsekuensi ketika ‘kepentingan diri’ diletakkan pada altar sucinya. Dan kemudian dibaptis sebagai satu-satunya ‘yang rasional’. Di kemudian hari Amartya Sen mengajukan kritik terhadap hal ini. Dikatakan Sen, komitmen adalah juga ‘yang rasional’. Bahkan jika itu dilihat dari sudut ‘kepentingan diri’ sekalipun.
Accumulation by dispossession memiliki beberapa fitur, antara lain privatisasi-komodifikasi, finansialisasi, managemen dan manipulasi krisis, dan soal state redistributions. Beberapa pemikir menambahkan soal mass incarceration, katakanlah kriminalisasi terutama terhadap kaum miskin dan terpinggirkan (karena AbD tadi). Mungkin juga ini adalah ‘solusi mereka’ terhadap apa yang disebut Karl Polanyi dalam The Great Transformation (1944) sebagai ‘double movement’ atau gerakan ganda. Gerakan pertama adalah ‘akumulasi ugal-ugalan’, dan kakayaan kemudian cenderung mengumpul pada sedikit pihak saja. Gerakan kedua adalah upaya-upaya untuk melawan hal di atas, terutama melalui kebijakan-kebijakan negara. Maka tak mengherankan pula kaum neolib senang dengan istilah ‘ultra-minimal state’. Agak curang sebenarnya, untuk bebasnya lalu-lintas modal mereka demen yang ultra-minimal bahkan kalau perlu para diktator itu diturunkan di bagian akhir abad-20 lalu itu, tetapi ketika kepentingan modal atau akumulasi perlu kebijakan negara maka dibayangkanlah negara yang ‘ultra-maksimal’. Curang. Termasuk juga soal tarif-tarif hari-hari ini.
Dari Toynbee kita bisa belajar bahwa budaya yang ‘nilainya rendah’ akan lebih mudah masuk dibanding dengan yang nilainya ‘tinggi’. Bukannya ‘get on your bike’[2] yang terus dibangun ekosistemnya, tetapi terus saja soal pat-gu-li-pat, kong-ka-li-kong dikembangkan, beranak-pinak. Bukannya ke-sekte agung-an (famous sect) kayak Thatcher tetapi pengelola negara justru banyak yang menjadi serakah, tak tahu batas. Bahkan komitmen-pun diolok-olok habis-habisan.[3] Akhirnya benar-benar hanya kepentingan diri (dan kroninya) yang penting. Sama sekali tidak mengenal apa itu komitmen, paling tidak seperti dibayangkan oleh Amartya Sen. Selama (kegilaan) kepentingan diri itu diberi ‘umpan’ maka tegaklah rejim, begitu kira-kira ‘paradigma’ bertahun terakhir. Tegak sama sekali bukan karena komitmen (atau bisa dibaca juga, prestasi), tetapi lebih karena patronase. Sik-patron yang suka tebar ‘umpan’ itu. Maka merampoklah mereka-mereka itu, dengan tanpa beban lagi. Enteng-enteng saja merampok dana (kolektif) pensiun melalui lika-liku finansialisasi yang super licik. Enteng-enteng saja merampok segala kekayaan republik dengan menganggap republik sebagai res-privat. BUMN menjadi tempat penjarahan, dan ujungnya nanti adalah privatisasi ugal-ugalan. Atau lihat bagaimana menggiurkannya koperasi desa di tangan orang-orang miskin komitmen. Juga, enteng-enteng saja mereka melakukan mass incarceration: kriminalisasi bagi yang melawan perampokan, perampasan, terutama pada rakyat kecil. Intinya, rejim ‘orang baik-sederhana’ bertahun terakhir itu memang pada dasarnya adalah ‘rejim rampok’. Dan itu juga yang mau dilanjutkan melalui tangan-tangan termul (ternak-mulyono) di kabinet sekarang ini. Memang tidak mudah dilawan karena yang dihadapi sudah sampai pada tahap kegilaan. Tidak mudah, tetapi tentu bukannya tidak mungkin. Maka hanya ada satu kata, menurut Widji Tukul: “Lawan!” Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, demikian kata Tom Lembong. *** (04-08-2025)
[1] https://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu
[2] Ungkapan dari Norman Tebbit, salah satu menterinya Thatcher, di tahun 1981
[3] https://www.pergerakankebangsaan.com/405-Ayo-Komit-nang-Kebon/, tulisan ini didorong ketika Jokowi sebagai presiden ditemui oleh tokoh-tokoh yang khawatir terkait pelemahan KPK. Dijawab Jokowi supaya tokoh-tokoh itu tidak khawatir soal komitmennya dalam pemberantasan kosupsi. Dan kita tahu sekarang, itu cuma ngibul doang, korupsi justru meluas dan membesar dalam luasan dan jumlah yang tak terbayangkan sebelumnya.


1733. Cerdas Bersama Manusia Merdeka
1734. Spiral Lainnya
05-08-2025
Sekitar 1970-an, Dom Helder Camara mengintrodusir istilah spiral kekerasan. Camara adalah seorang Uskup dari daerah utara-timur Brazil yang masih penuh dengan kemiskinan saat itu. Tahun-tahun sekitar itu sedang berkembang pula yang kemudian dikenal sebagai Teologi Pembebasan. Jadi istilah spiral kekerasan lahir tidak di ruang kosong, tetapi sungguh dekat dalam keseharian. Kemiskinan yang sebenarnya juga salah satu bentuk utama dari ketidak-adilan itu perlahan akan membangun reaksi, ingin lepas dari kemiskinan-ketidak-adilan, macam-macam aksinya. Bisa melalui unjuk rasa misalnya. Tetapi unjuk rasa ini kadang direspon oleh penguasa dengan represi yang justru memperparah ketidak-adilan. Maka reaksipun semakin meningkat dan masuklah pada spiral kekerasan yang semakin lama semakin keras. Dan ketidak-adilanpun semakin dalam juga. Kekerasan ini bisa menampakkan diri dalam bentuk telanjangnya, katakanlah dalam bentuk hard-power.
Bertahun terakhir nampaknya republik ‘menghadirkan spiral lainnya’, ‘spiral pembodohan’. Beberapa indikasi bisa ditunjuk dalam hal ini. Yang sungguh telanjang bagaimana dunia pendidikan memang sedang dirusak. Di semua tingkat, paling tidak dengan ditunjuknya petinggi departemen yang sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan dunia pendidikan, misalnya. Dan keluarannyapun terbukti amburadul. Sayangnya juga, bahkan perguruan tinggipun diobok-obok, ‘dibunuh karakternya’ sebagai lembaga tinggi yang sebenarnya terhormat. Lihat misalnya yang beredar hari-hari ini, penampakan seorang professor (Prof. K) dari perguruan ternama (dan tua) dengan logika yang acakadut. Benar-benar prototipe ketika hasrat telah memperbudak rasio habis-habisan. Sebuah olok-olok, sebuah pembunuhan karakter bagi perguruan tinggi yang (sebenarnya) terhormat. Kebetulan? Tidak-lah.
Selebritisasi dunia politik adalah juga indikasi dari ‘spiral pembodohan’ ini. Bagi banyak pemikir, politik semestinya ada dalam ranah ‘rasio’. Katakanlah itu ‘syarat mutlaknya’, dan memang belum mencukupi. Kadang perlu ‘panggung sandiwara’ juga, kadang main-main seperti seorang selebriti juga, tetapi tetap saja: jangan dibalik. Politik semestinya menjadi salah satu ‘puncak’ dari animal rationale. Maka menjadi politisi adalah jalan panjang dan terjal, karena ia harus melawan dalam dirinya kecenderungan seperti dikatakan Freud, bahwa justru tindakan kita akan banyak dipengaruhi oleh ‘bawah sadar’. Selebritisasi yang sudah tidak tahu batas dalam ranah politik bisa dilihat ketika ada yang dengan segala cara ingin selalu tampil di ruang publik. Bahkan jika masuk dalam kontroversipun akan dijalani pula, berulang dan berulang. Dari bagi-bagi skin-care sampai tanpa malu mengajukan diri sebagai ‘korban’, berulang dan berulang. Macam-macam. Masih banyak yang bisa disebut dalam ‘spiral pembodohan’ ini. Sebenarnya ‘spiral pembodohan’ ini sedikit banyak tergambarkan pada apa yang pernah dikatakan Napoleon: “When small men attempt great enterprises, they always end by reducing them to the level of their mediocrity.”
Ada yang ‘meragukan’ apakah ini termasuk ‘spiral kekerasan’ atau ‘spiral pembodohan’, tetapi apapun itu keluarannya sama, ketidak-adilan, yaitu yang disebut sebagai mass incarceration atau kriminalisasi (rakyat kecil yang dipaksa ‘minggir’). Rakyat kecil yang mengambil dahan kering diperkebunan untuk kayu bakar kemudian dipenjara sekian bulan. Rakyat menemukan bibit unggul dengan caranya sendiri, dipenjara sekian tahun atas nama hak cipta. Tebang pilih itu tidak hanya membodohkan, tetapi juga salah satu bentuk kekerasan yang maunya ‘mendisiplinkan’ siapa saja yang menolak ketidak-adilan. Bahkan tidak hanya ‘rakyat kecil’, tetapi juga misalnya Tom Lembong. Tebang-pilih yang maunya untuk mendisiplinkan siapa saja yang berseberangan. Dan itu ternyata juga sungguh membodohkan khalayak kebanyakan. Lihat bagaimana alur (pembodohan) logika itu dibangun selama (sembilan bulan) persidangan. *** (05-08-2025)