1765. Asing Yang Tidak Tergantung Kita
03-09-2025
Sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang ini, ‘yang luaran’ itu akan selalu ‘merecoki’ republik, seakan memang tidak tergantung kita lagi. Mau kita lihat sambil koprol atau kayang-pun tetap itu tidak tergantung pada kita. Menjadi merdeka adalah membuat ranah yang memberikan kemungkinan apa-apa yang tergantung pada kita bisa diupayakan bersama. Maka narasi -katakanlah begitu, sebelum kemerdekaan di tangan dan setelah di seberang jembatan emas mestinya akan berbeda ketika bicara ‘yang luar-luar’ itu. Bukan karena ‘yang luar’ berhenti ‘mengganggu’ tetapi karena apa-apa yang tergantung kita itu sungguh perlu per-hati-an lebih. Tidak jauh dari apa kata Maciavelli ketika bicara soal keberuntungan dalam kekuasaan. Keberuntungan yang seakan mau-maunya semesta itu bisa dibayangkan sebagai separuh nasib dari orang tertentu. Atau peristiwa tertentu. Separuhnya? Machiavelli bicara soal virtue, terutama terkait timbang-menimbang dalam membangun respon terhadap situasi yang terus berkembang. Kita mungkin mendapat keberuntungan di tengah-tengah chaos, tetapi untuk membangun ‘kosmos’ itu tergantung kita. Pelajaran hari-hari ini adalah pelajaran dimana ada yang begitu yakin keberuntungan tetap melekat pada diri (selamanya), lupa membangun ‘kosmos’ ketika situasi terus berubah. Maka yang terjadi adalah chaos yang terus membayang dan tersembunyi, yang hari-hari ini meledak secara telanjang.
Matahari kembar seperti sudah diperingatkan oleh SBY adalah peringatan terhadap kemungkinan retaknya ‘kosmos’. Sik-kembaran itu memang sudah ndableg, sudah begitu yakin bahwa keberuntungan akan selalu melekat dalam dirinya, di lain pihak bertahun yang dijalaninya dapat dilihat dengan telanjangnya bagaimana ia meminggirkan timbang-menimbang secara telak. Tak mengherankan seakan ia selalu saja membawa potensi chaos di dalam tas jinjing kesayangannya. Dibawa kemana-mana. Sadar atau tidak. Bahkan bertahun apa yang dilakukan dalam mengacak-acak ‘kosmos’ republik menampakkan diri seakan ia sedang membangun ‘rejim pembuka kotak Pandora’ saja. Hasilnya? Salah satunya adalah korupsi merebak dalam keluasan dan jumlah yang tak terbayangkan sebelumnya. Belum hancurnya bermacam lembaga yang bisa saja itu sebenarnya adalah bagian penyangga dari ‘kosmos’ republik.
Apa yang mau dikatakan di sini adalah, ‘pemimpin’ yang sibuk merawat keberuntungan diri dan lupa menjaga ‘kosmos’ dihadapan situasi yang terus berubah, ia mempunyai potensi besar untuk bersekutu dengan ‘chaos’, termasuk chaos yang dibawa oleh ‘yang luar-luar’ itu, persis seperti sebelum jembatan emas terbangun. ‘Yang luar-luar’ itu, yang terus saja akan ‘merecoki’ republik -dari arah manapun anginnya berembus, tiba-tiba saja akan menemukan ‘sekutu potensial’nya. Sekutu yang sama-sama ada dalam dataran chaos. Itulah hal kedua dari peringatan SBY terkait dengan ‘matahari kembar’ yang akan berujung retaknya ‘kosmos’ republik itu.
Hal ketiga adalah apa yang disebut ‘kosmos’ itu bukanlah sebuah ‘harmoni tenang-tenang saja’, tetapi jika memakai istilah si-Bung, ia penuh dengan romantika, dinamika, dan dialektikanya -kadang disingkat sebagai rodinda. Semestinya. Atau kalau kita memakai alur Machiavelli terkait keberuntungan di atas, keberuntungan itu adalah soal romantika, sedang separuh yang semestinya dijalani dengan virtue, itulah dinamika dan dialektika. Sik-kembaran bertahun-tahun bisa dilihat lebih sibuk dalam romantika, bahkan bisa dikatakan juga ‘sihir’. Yuniornyapun demikian, lihat bagaimana drama bertemu dengan ‘perwakilan ojol’ dan bagi-bagi sembako hari-hari ini. Sama sekali tidak menampakkan diri sebagai yang trampil dalam ber-dinamika dan berdialektika. Tetap saja mainnya sebatas romantika. Adanya kembaran itu membuat dinamika dan dialektika menjadi ‘tidak fokus’, bahkan bisa-bisa ‘salah kostum’, dengan terjebak dalam romantisme anti-asing, misalnya. Maka bagi republik hari-hari ini, adalah penting untuk (segera) menyingkirkan sik-matahari kembar itu. Selain karena kebiasaan buruk yang digendongnya, yang lebih utama adalah supaya bisa menjadi lebih fokus untuk ber-dinamika dan ber-dialektika itu. Kritik bisa langsung ‘tepat sasaran’, misalnya. *** (03-09-2025)
1766. Mengapa KPU
04-09-2025
Berapa jumlah anggota KPU pusat? Tidak lebih dari sepuluh. Demikian juga Bawaslunya. Maka akan ‘lebih mudah’ membangun KPU (dan Bawaslu) yang kredibel dari pada mengharapkan partai politik berbenah diri, misalnya. Semestinya. Berangkat dari (hanya) kasus ijazah palsu itu saja sudah cukup alasan untuk merombak total KPU (dan Bawaslu) sekarang ini. Mumpung belum kalah atau terdesak atau teralihkan oleh gegap gempitanya pemilihan. Merombak total KPU (dan Bawaslu) dapat memberikan angin segar terkait dukungan terhadap demokrasi dari pemerintah baru ini, yang baru saja babak belur kemarin-kemarin itu.
Beranikah rejim ini mendukung misalnya, pakar-pakar yang terlibat dalam Dirty Vote (2024) untuk menggunakan segala pengetahuan, integritasnya, dan tentu keberaniannya dalam membangun demokrasi melalui lembaga KPU dan Bawaslu? Atau pakar, praktisi pembela demokrasi lainnya yang sudah teruji? Atau juga ahli-ahli IT terbaik republik yang berani mendukung penyelenggaraan pemilihan yang jurdil dan terbuka dengan sistem informasinya? Dan berani bertanggung jawab, berani untuk diuji sistem informasi yang dibangunnya oleh ahli-ahli lain di depan publik? Jika negara adalah sebuah panggung teater, beranikan rejim baru ini menampilkan pertunjukan yang berbeda dan lebih bermutu di atas panggung? Dengan lakon lebih menampilkan kuatnya akal sehat dan kehormatan, integritas? Bertahun terakhir yang banyak pethakilan di atas panggung adalah segala hasrat gelap, terutama hasrat akan uang. Bermacam bentuk kemewahan seakan sengaja mengambil porsi besar tampil dalam pertunjukan.
Ada argumentasi mengapa lempar-lempar bingkisan dari pejabat itu terus saja dilakukan dengan tanpa beban, alasannya: karena khalayak ternyata suka-suka saja tuh. Atau menggunakan ‘rata-rata IQ’ sebagai pembenaran melakukan hal-hal ‘konyol’ di depan publik. Lupa bahwa berapapun ‘rata-rata IQ’, semua saja akan mempunyai kemampuan untuk belajar. Apalagi jika konteksnya ‘belajar bersama’. Yang diperlukan adalah ruang dan waktu untuk ‘belajar bersama’ itu. Lihat beberapa waktu lalu ketika sebagian ruang publik menghadirkan ruang belajar-pertunjukan ‘Desak Anies’ itu. Jika hal seperti itu mendapatkan waktu yang luas dan panjang, maka yakinlah ketika ada pejabat yang masih saja lempar-lempar bingkisan sambil pecingas-pecingis, bingkisan akan dilempar balik pada pejabat itu. Tepat menimpuk wajah pecingas-pecingisnya itu.
Marah adalah salah satu hal wajar dalam bermacam emosi manusia. Jika kebablasan maka memang kadang perlu anger management, kata Jack Nicholson. Tetapi di sisi lain, kemarahan bisa menjadi bagian penting dari apa yang disebut Henry Bergson sebagai elan vital itu, energi hidup. Elan vital yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah creative evolution. Jadi memang di ujung sananya akan berbeda dengan penganut garis keras ‘ideologi’ survival of the fittest a la Charles Darwin itu.
Salah satu upaya menjaga dan mengembangkan creative evolution dalam hidup bersama adalah dimulai dengan mengenal apa-apa yang ‘berdaya-ungkit’ besar. Dulu pernah dikenal istilah reformasi TNI, dan sekarang ini merebak istilah reformasi polisi, dan bukankah perlu ditambah juga reformasi partai politik? Tentu tidak boleh dilupakan juga, reformasi birokrasi. Tetapi fokus tulisan ini adalah pada KPU (dan Bawaslu), ‘revolusi’ KPU (dan Bawaslu).[1] Pertama tentu terkait dengan momentum. Yang utama: selesai! Bahkan dengan segala ‘kecurangan’, lupakan. Lupakan KPU (dan Bawaslu) sekarang ini. Dan bangun KPU (dan Bawaslu) baru diisi oleh sumber daya yang terbukti telah teruji, terutama dalam wawasan, integritas, dan keberaniannya. Bangun sistem informasi yang mempunyai daya tahan, terutama terhadap ‘maksud jahat’, dan tentu siap diuji ulang. Dan jadikan ‘revolusi’ KPU (dan Baswalu) ini sebagai ‘patok duga’ terkait dengan keinginan rejim dalam mengembangkan demokrasi. Tetapi yang lebih penting adalah, menjaga elan vital yang sudah terbangun dengan salah satunya melalui ‘katalis’ kemarahan baru-baru ini. Siap ‘marah’ lagi ketika ternyata semua kembali pada omon-omon belaka. Marah dan marah lagi! *** (04-09-2025)
[1] https://pergerakankebangsaan.org/tulsn-138, nomor 1763: “Gelombang Berikutnya: KPU!”
1767. Republik Rasa Karnaval
04-09-2025
Dalam American English, sejak 1926 carnival berarti ‘a circus or amusement fair’.[1] Karnaval asal usul katanya dari carnival ini. Karnaval dalam KBBI berarti ‘pawai dalam rangka pesta perayaan’. Dalam Google Books Ngram Viewer, nampak dalam grafik kata carnival mengalami lonjakan secara terus menerus sejak tahun 1980.[2] Iseng-iseng, bandingkan dengan kata brutal yang menampakkan grafik serupa.[3] Mungkin saja tidak ada hubungannya, kebetulan saja, tetapi iseng-iseng kita bisa bertanya, ada apa dengan tahun 1980? Tahun itu adalah naiknya Ronald Reagan jadi presiden AS. Setahun sebelumnya, Margaret Thatcher naik jadi PM Inggris, dan kita tahu bahwa mulai saat itu paradigma neoliberalisme mulai merebak. Yang sebelumnya ‘diuji-coba’ dulu di Chile setelah penggulingan Allende, melalui operasi dengan kata sandinya: Operasi Djakarta. Atau ada yang bilang, Djakarta Method, di tahun 1973-an.
David Harvey di penghujung abad-20 melihat ada perkembangan cara akumulasi dalam neoliberalisme dibandingkan bentuk kapitalisme sebelumnya. Sebelumnya lebih apa yang disebut Marx sebagai akumulasi primitif, sedangkan dalam neoliberalisme berkembang pula accumulation by dispossession, dengan fitur-fiturnya antara lain, privatisasi, finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, soal state redistributions, dan ada yang menambahkan: mass incarceration. Pierre Bourdieu dalam sebuah tulisannya (1998) mengatakan bahwa neoliberalisme itu pada dasarnya adalah a programme for destroying collective structures which may impede pure market logic.[4] Thomas Piketty dalam bukunya Capital in the Twenty-First Century (2014) menyampaikan data-data bagaimana ketimpangan menjadi semakin lebar. Bagaimana konsentrasi kekayaan 1% kelas paling atas itu meningkat drastic sejak tahun-tahun 1980an itu. Termasuk dicontohkan juga, Indonesia. Padahal buku itu terbit tahun 2014, belum memasukkan data sepuluh tahun terakhir ini.
Maka, mungkin saja naiknya kata carnival dan brutal sejak tahun 1980 seperti dinampakkan dalam grafik Google Books Ngram Viewer seperti disinggung di atas bukanlah kebetulan saja. Bukankah kata sandi ‘Operasi Djakarta’ sekitar 50 tahun lalu itu ada dalam bayang lekat kebrutalan? Kudeta yang berujung terbunuhnya presiden terpilih demi ‘lancarnya’ sebuah paradigma ekonomi tertentu? Dan jangan-jangan segala kebrutalan dalam ‘menapak jalan’ terkonsentrasinya kekayaan di tangan 1% itu memang membutuhkan segala bentuk ‘karnaval’ itu? Supaya apa yang disebut Karl Polanyi sebagai ‘gerakan ganda’ (double movement) dalam The Great Transformation (1944) tidak manifest?
Apalagi ada pendapat Guy Debord di tahun 1967 tentang the society of the spectacle. Ditambah dengan buku Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali, terbit pertama kali tahun 1980. Maka tidak mengherankan jika bertahun terakhir ini ada yang begitu trampil dalam meracik republik menjadi ‘rasa karnaval’ saja. Bagaimana isu mobil Esemkapun kemudian di-‘karnaval’kan dengan begitu hebohnya. Atau bagaimana seorang petinggi kemanapun pergi selalu membawa rombongan kamera dengan banyaknya. Atau bagaimana keranjingannya akan bermacam kerumunan. Maka alih isu-pun berkembang menjadi semacam industri sendiri. Bermacam pethakilan itu, bermacam glécénan hèpi-hèpi itu, ataupun segala jogat-joget itu, tiada lain jika memakai apa yang disinggung oleh Thomas Piketty di atas, demi lancarnya konsentrasi kekayaan di tangan sekitar 1% saja. Biar accumulation by dispossession menjadi lancar, ngeri-ngeri sedap-lah.
Terlalu banyak, terlebih sepuluh tahun terakhir, bagaimana accumulation by dispossession itu berjalan bahkan dengan kasarnya. Tanpa sungkan lagi, tanpa beban lagi. Karena merasa yakin republik sudah menjadi rasa karnaval saja. Mudah ditipu, mudah dialihkan. Lupa bahwa ada yang namanya ‘tacid knowledge’ itu. Pengetahuan yang kadang tidak mudah diungkapkan, tetapi jelas ada dalam kesadaran. Termasuk terkait dengan segala kesenjangan yang nyata di depan mata. Juga kejengkelan akan segala ‘karnaval’ hèpi-hèpi pamer kemewahan dari pejabat publik. Padang rumput kering yang tinggal menunggu percikan api sehingga menjadi terbakar hebat. Dan ‘mereka-mereka’ itu bukannya tidak tahu akan kondisi itu. ‘Mereka-mereka’ itu pada dasarnya trampil juga dalam membangun ‘story telling’ seperti pernah dikatakan oleh David C. Korten. Termasuk dalam hal ini, cerita soal ‘kambing hitam’. Tak jauh dari hikayat-nasib Remirro de Orco yang diceritakan Machiavelli dalam Sang Penguasa: “Cesare menunggu kesempatan baik ini. Kemudian, pada suatu pagi, tubuh Remirro ditemukan terpotong dua di lapangan Cesena bersama sepotong kayu dan sebilah pisau berdarah di samping tubuhnya.”[5] Brutal. *** (04-09-2025)
[1] https://www.etymonline.com/word/carnival
[2] https://books.google.com/ngrams/graph?content=carnival&year_start=1800&year_end=2022&corpus=en&smoothing=3
[3] https://books.google.com/ngrams/graph?content=brutal&year_start=1800&year_end=2022&corpus=en&smoothing=3
[4] https://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu
[5] Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, Penerbit Gramedia, 1987, hlm. 30
1768. Dua Tulisan Lama
05-09-2025
Low Back Pain, M54.5
https://www.pergerakankebangsaan.com/599-Low-Back-Pain-M54-5/
Abbas Attar
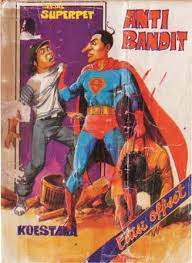
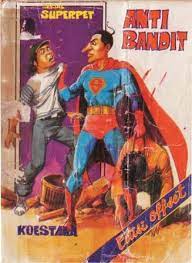
1769. Tendo Achilles Kaum Semau-maunya
06-09-2025
Dalam bermacam komunitas, orang sakti biasanya mempunyai satu titik kelemahan. Demikian juga tokoh sakti Achilles dalam cerita Yunani Kuno, kelemahannya ada di kaki bagian bawah belakang. Nama tendo Achilles berasal dari hikayat itu. Tendo seperti juga jaringan otot yang ‘dilengkapinya’ jika dilihat di bawah mikroskop maka nampak tidak terdiri yang tunggal-tunggal saja. Katakanlah ia seakan sebuah bundle. Kaum semau-maunya di ranah negara itu juga punya tendo Achillesnya sendiri, yang membuat dirinya tegak tetapi sekaligus jika itu ‘dipanah’ hingga putus maka akan terseok-seoklah dia. Bahkan bisa jadi lumpuh tersungkur.
Apa yang menjadi tendo Achilles kaum semau-maunya di ranah negara? Meminjam istilah jaman old itu adalah ‘jalur ABG’ itu, jalur A(bri), B(irokrasi), dan G(olkar). Atau bisa kita bayangkan, gabungan antara hard power dan soft power, sekali lagi ini di ranah olah kuasa negara. Yang hari-hari ini membuat kita sadar bahwa dalam ABRI jaman old itu, lembaga kepolisian masuk di dalamnya. Jadi yang sering terdengar ‘tentara kembali ke barak’ itu rasanya masih kurang lengkap juga. Dan kaum birokrat itu ternyata juga meluas sampai pada jajaran di yudikatif dan legislative. Lihat misalnya kasus ‘makelar kasus’ di MA itu, katakanlah sekuat-kuatnya integritas seorang Hakim Agung terpilih, ia tetap saja bisa tergoda oleh para ‘makelar kasus’ yang ada di antara kaum birokrat di sana (ingat kasus sik-sekretris MA itu). Atau bahkan yang freelance. Demikian juga sik-Jaksa Agung, atau juga sik-anggota parlemen, baik yang ada di DPR atau DPD.
Bagaimana dengan ‘jalur G’ dimana sekarang sudah dimungkinkan banyak partai berdiri? Kita bisa membayangkan juga bagaimana kader-kader sik-G ini sekarang banyak yang mendirikan partai di luar G, tetapi apapun itu, sekarang sudah bebas mendirikan partai politik. Paling tidak. Maka masalah ‘jalur G’ ini semestinya kita geser ke KPU (dan Bawaslu). Jika kita hari-hari ini kembali berteriak (lagi) ‘reformasi TNI’, ‘reformasi birokrasi’, ditambah dengan ‘reformasi Kepolisian’, maka perlu ditambah lagi: ‘reformasi KPU (dan Bawaslu).
Bagaimana dengan ‘kekuatan uang’? Uang bisa dikatakan sebagai salah satu ‘pedang di tangan’. Tetapi setajam-tajamnya pedang, ia tidak akan pernah menjadi ‘tendo achilles’. Jika ke-empat reformasi di atas dan tendo Achilles kembali pada apa yang semestinya republik sebagai ‘negara yang berdasarkan hukum’, maka ‘kekuatan uang’ semestinya akan mengayun ke arah lain. Bukan lagi dengan penuh kekuatan yang justru membabat habis bakat-bakat terbaik republik di ranah negara.
Menurut Pierre Bourdieu, tindakan akan dipengaruhi oleh capital, habit, dan ranah (field). Maka ungkapan bahwa ikan busuk mulai dari kepala itu lebih mengarah pada capital (modal). Yang dimaksud dengan capital atau modal ini lebih pada ‘modal simbolik’. Di sebuah klinik, siapa pemegang ‘modal tertinggi’? Yang kemana-mana bawa stetoskop itu misalnya, sik-dokter. Di ruang kuliah, di ranah ruang kelas: dosen atau guru. Maka jika kemudian membiak dan merebaknya ‘kaum semau-maunya’ ini, mempunyai alasan kuat untuk melihat perilaku dari yang mempunyai modal atau capital (simbolik) tertinggi itu. Jika bertahun lalu ada yang ‘jualan’ revolusi mental dan ternyata laku keras, itu nampaknya jauh dalam kesadaran khalayak kebanyakan sudah merasa ada habit yang perlu diubah. Habit yang dimaksud Bourdieu lebih dari sekedar ‘kebiasaan’, tetapi ia sudah ada di ‘ruang antara’ antara kebiasaan dan ‘arketipe’.
Jika kita bicara ranah negara, bisa dikatakan bahwa capital atau modal di atas adalah juga ‘prakondisi politis’, ranah atau field adalah ‘prakondisi teknis’, dan habit adalah ‘prakondisi sosial’. Kita bisa melihat bagaimana jika pemegang capital tertinggi mempunyai ‘maksud-maksud baik’, demikian juga khalayak kebanyakan juga memberikan dukungannya, tetapi ‘prakondisi teknis’ di bermacam ranah yang disebut di atas (ke-empat yang mestinya direformasi) tetap saja rigid tak mau berubah juga? Sudah terlalu lama ‘mapan’ sebagai tendo Achilles-nya ‘kaum semau-maunya’ rejim sebelumnya? Itulah dalam dua tulisan terdahulu disinggung soal KPU (dan Bawaslu), hal yang semestinya ‘lebih mudah’ di-reformasi dibanding lainnya. Mulailah dengan KPU (dan Bawaslu), selain ‘lebih mudah’ juga sekaligus langsung ‘menembak’ tendo Achilles sik-’kaum semau-maunya’ yang masih saja pethakilan itu. Semau-maunya seakan menjadi ‘yang maha kuasa’ dalam mengatur-menentukan nasib seseorang dalam sebuah pemilihan. *** (06-09-2025)
