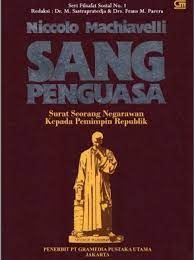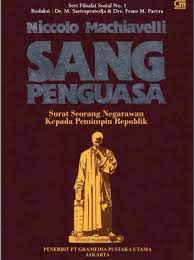1835. People Power Di Tengah Dua Matahari
28-12-2025
"A pure democracy may possibly do, when patriotism is the ruling passion; but when the State abounds with rascals, as is the case with too many at this day, you must supress a little of that popular spirit." (Surat Edward Rutledge ke John Jay, 24 November 1776)[1]
People power bisa dibayangkan kurang lebihnya ada dalam ranah supress a little of that popular spirit, meski sebenarnya tetaplah itu (people power) mesti diyakini sebagai bagian dari demokrasi juga. Hanya saja menampakkan diri di luar ‘prosedur normal’-nya. Ketika berurusan dengan ‘gerakan orang banyak’ memang harus hati-hati. Bukan masalah akan ditunggangi atau tidak, tetapi ketika massa terbentuk sering muncul ‘kekaburan-kekaburan’ tersendiri. Maka sejak awal memang harus jelas siapa saja sik-rascals-nya, sik-sasaran utama people power. Apalagi dalam situasi dengan ‘matahari kembar’ yang seakan bersinar sama terangnya. Dimana kebanyakan para rascals itu lebih banyak bersembunyi? Di balik ‘matahari A’ atau ‘matahari B’? Tentu ini ada nuansa ‘spekulasi’, tetapi ini juga soal mana yang masih bisa diharapkan dan yang sama sekali tidak. Soal harapan tersisa, dan satunya: yang sudah terbukti bertahun-tahun justru sebagai ‘pembunuh harapan’, khas salah satu karakter dari kaum rascals di ranah negara.
Keluarnya keputusan Komisi Yudisial berupa sangsi terhadap hakim-hakim sidang Tom Lembong dulu itu, memberikan sedikit harapan terkait dengan perbaikan lembaga peradilan. Keputusan sangsi itu keluar setelah Komisi Yudisial baru dilantik sekitar awal Desember lalu. Tetapi kita juga bisa membayangkan apa-apa di belakang mengapa para ‘bintang’ dan juga yang sudah purnawirawan di BNPB itu misalnya, terkait dengan bencana banjir di Sumatera, bicaranya seakan di luar harapan normalnya warga negara. Mulai dari “itu hanya mencekam di medsos, tak ada penggundulan hutan, listrik sudah menyala, sampai dengan ‘himbauan’ supaya memberitakan atau mengunggah hal-hal baik saja”. Bahkan termasuk yang berpangkat kapten itu (cat. sudah naik pangkat, bukan kapten lagi, cuk). Jika membayangkan hitung-hitungan ‘kekuatan kekerasan’, apa yang menampakkan diri melalui ujaran-ujaran ‘para bintang’ di atas, sedikit banyak kita bisa membayangkan bahwa ‘kekuatan kekerasan’ itu belumlah sepenuhnya di tangan ‘panglima tertinggi’-nya. Apalagi jika ditambah dengan yang pegang senjata tetapi sipil itu. Yang direncanakan untuk direformasi tapi malah dengan terang-terangan ‘menantang’ di depan hidung. Bagi yang berpuluh tahun hidup dalam ‘kekuatan kekerasan’ hitung-hitungan seperti itu tidak hanya penting dan sentral, pastilah juga akan cukup menggetarkan. Tetapi apakah kemudian kita menjadi maklum-maklum saja? Yang pasti, apapun itu yang namanya kesabaran tentu ada batasnya.
Siap mati untuk rakyat tentu kata-kata yang menggetarkan. Bahkan akan dengan spontan mengundang tepuk tangan. Tetapi bagi khalayak kebanyakan, bukan ‘kematian heroik’ yang ditunggu, tetapi lebih pada apa keputusan, tindakan yang kalau itu dilakukan memang mempunyai resiko kematian semakin mendekat. Bagaimanapun kematian itu adalah sebuab kepastian, mau heroic atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah apa keputusan dan sikap di depan kematian itu. Sebelum kematian menjemput -entah kapan itu, bermacam kemungkinan terhampar di depan mata, mana yang akan dipilih? Apakah ia memilih sebagai orang bebas, misalnya? Maka jika ‘siap mati untuk rakyat’ belajarlah dari seorang ibu, ia ‘siap mati’ untuk sebuah kelahiran baru. Pertanyaannya adalah, apa yang diputuskan dan dijalankan demi sebuah ‘kelahiran baru’ di ranah negara? Bagi Hannah Arendt, politik merupakan interaksi dari manusia-manusia bebas, dan dengan segala kapasitas dirinya ia bersama-sama lainnya menyingkap apa yang tersembunyi: potensi untuk sebuah kelahiran baru. Dan itulah esensi dari demokrasi sebenarnya.
Di atas disinggung pentingnya sangsi dari KY terhadap hakim-hakim persidangan Tom Lembong, mengapa? Karena dalam salah satu pilar rejim sontoloyo terdahulu, sandera kasus, peradilan menempati posisi sentral. Salah satunya melalui ‘ancaman’ dari lembaga peradilan. Tetapi ini baru separuh kebenaran, separuhnya itu adalah penegasan bahwa ‘ia’ adalah sik-godfather. Mafia yang siap memberikan perlindungan (dan diganti dengan kesetiaan), termasuk lembaga peradilan yang selalu siap dimainken dalam hal ini dan segala apparat yang terlibat dalam penegakan hukum pada umumnya. Maka kembali pada pertanyaan di atas, people power itu ‘menyasar’ pada ‘matahari’ yang mana? Yang dengan segala upaya justru sudah terbukti menolak sebuah kelahiran baru? Status quo? Status quo yang jelas semakin nampak terus saja membunuh harapan dengan tanpa beban lagi, sambil pecingas-pecingis itu, terutama terhadap generasi mudanya? *** (28-12-2025)
[1] https://www.pergerakankebangsaan.com/304-Surat-Edward-Rutledge-ke-John-Jay-24-Nov-1776/
1836. MBG Saat Libur Sekolah
30-12-2025
Job security adalah upaya dalam ranah pekerjaan dimana pekerjaan diharapkan mampu memberikan rasa aman tidak hanya sekarang tetapi juga di masa depan. Bagaimana ‘rasa aman’ itu ikut ditopang juga dengan pekerjaan, dan dengan itu pula tidak sekedar mampu menjalani hidup tetapi juga mengembangkan diri, dan keluarga. Dalam paradigma neoliberalisme, job security ini mengalami tantangan serius, paling tidak dalam istilah flexible job bisa dilihat tantangan itu. Jika dilihat lebih jauh itu didasarkan pada penghayatan survival of the fittest yang sudah menjadi semacam ideologi. Dan titik berangkatnya adalah ‘kebebasan individu’. Yang mau dikatakan di sini adalah, bahkan ketika kita bicara soal security-pun bisa dirunut apa latar belakang atau ‘paradigma’ yang lekat dalam bangunannya. Bangunan seperti apa yang sedang dibangun.
Beberapa waktu lalu ada psikolog yang bercerita bahwa mulai ada yang masuk ruang praktek dengan keluhan gelisah melihat bagaimana republik dikelola. Kita bisa bayangkan bagaimana ‘dunia kehidupan’ keseharian itu ternyata tidak memberikan ‘rasa aman’ sehingga terus-menerus mengganggunya. Apalagi dengan berkembang sosial-media seperti sekarang ini, in-formatio yang mendekat pada dirinya banyak yang terlalu ‘simpang-siur’. Semestinya dengan segala simpang-siur itu, republik bisa menjadi ‘pembanding’ sehingga rasa aman tetaplah dimungkinkan. Republik yang dikelola tidak dengan ‘simpang-siur’. Maka ‘MBG saat libur sekolah’ bisa menjadi studi kasus, apakah ini juga menjadi bagian dari ke-simpang-siuran yang ujungnya meretakkan ‘rasa aman’ dan katakanlah mendorong munculnya ‘gangguan mental’ khalayak kebanyakan?
Jika kita jengkel terhadap segala pernak-pernik penjelasan tentang ‘MBG di masa liburan sekolah’ yang keluar dari para bacot petinggi BGN, tentu itu terkait juga dengan sejarah pembacotan sebelum ini. Banyak bisa diundang lagi jejak-jejak digitalnya. Bahkan sebenarnya itu adalah sebuah ‘pola umum’ dunia perbacotan dari petinggi, orkes asal mangap asal njeplak sebagai bagian dari tirai tebal dalam menyamarkan laku-laku koruptif. Pentingnya ‘strategi’ ini bisa dilihat bagaimana sampai-sampai sandera kasus itu salah satu indicator ‘penyerahan diri’ total-nya adalah: mau melontarkan hal asal mangap asal njeplak, termasuk memakai bahasa tubuhnya. Siapa saja dengan tanpa beban mau ngebacot semau-maunya, ialah yang (paling) ‘loyal’ dalam dunia rejim yang dibangun oleh ‘mereka’. Rejim koruptif mereka, korupsi dalam segala bentuknya. Salah satu bagian tirai dalam bentuk sebagai ‘sasaran tembak’ atau jelasnya: sasaran tembak palsu. Bertahun-tahun ‘logika’ seperti itu dijalankan, diulang dan diulang. Ketika godaan uang dalam jumlah gigantisnya itu menjadi begitu menggoda, dijuallah jiwanya pada sik-iblis yang mau merusak republik sehingga menjadi semakin medah dan semakin mudah saja untuk dikuasai. Dikuasai ‘luar-dalam’-nya, segala kekayaan yang dikandung dalam perut ibu pertiwi.
Maka telah berlangsung bertahun-tahun banyak hal ngawur pendek akal, termasuk asal mangap asal njeplak, asal joget, asal panggul beras, asal adu, dan banyaaak lagi, semua itu ujungnya adalah pelemahan hidup bersama. ‘MBG saat libur sekolah’ adalah salah satunya. Emang loe siapa, kira-kira itu yang ada dalam alam pikir petinggi BGN ketika menghadapi bermacam masukan atau kritik. Tak jauh dari petinggi-petinggi lain. Mbudeg yang telah menjadi salah satu kebiasaan sontoloyo bertahun-tahun terakhir ini. Intinya, republik ini sedang terus saja dibuat bodoh. Maka hati-hati bagi yang menjadi keranjingan bicara (anti) asing-asing itu, ‘otentik’-kah itu? Jika itu ‘otentik’ maka ia akan sampai pada penghayatan bahwa apapun yang akan dilakukan oleh ‘osang-asing’ itu tidaklah tergantung pada kita. Asing mau kayang atau koprol itu suka-suka dia. Maka menjadi ‘otentik’ dalam hal ini adalah soal ‘yang tergantung’ pada kita, atau sik-dia yang sudah keranjingan bicara (anti) asing-asing itu. Apa yang masih bisa diharapkan jika yang sungguh tergantung pada dia -misal hak prerogratif, ia tidak (menjadi) bebas dalam mengelolanya? Juga pemberantasan korupsi misalnya. Apa yang masih bisa diharapkan? Ataukah pertanyaan-pertanyaan ini akan juga dijawab: emang loe siapa? *** (30-12-2025)
1837. Mati Karakter
31-12-2025
“Siap mati untuk rakyat!” demikian dikatakan oleh seorang jenderal serdadu. Serdadu atau tentara memang dilatih dari waktu ke waktu untuk berperang, untuk selalu berhadap-hadapan langsung dengan kematian. Kematian ‘yang sesungguhnya’, nyawa melayang, napas berhenti, tubuh tidak bergerak sama sekali, dan jika beruntung ia akan dimakamkan dengan diiringi tembakan salvo. Jika tubuhnya ditemukan. Mati dalam kehormatan yang (seharusnya) dibelanya. Sekali lagi, ‘mati sungguhan’. Tetapi dalam politik, kadang orang bisa ‘mati’ berkali-kali. Tetapi ada satu ‘kematian’ yang sulit untuk dibangkitkan lagi: ‘mati karakter’. Banyak contoh bagaimana tokoh politik itu mengalami ‘kematiannya’ ketika opini publik melihat ternyata ia berkarakter ‘sampah’ misalnya. Gary Hart yang digadang-gadang jadi calon presiden Partai Demokrat Amerika sono, pada pemilihan di tahun 1988, harus mengubur impiannya menjadi presiden bahkan sebelum bertarung. Karakter mak-nyusnya hancur gara-gara isu dengan Dona Rice, seorang model.
Maka ‘siap mati’ di ranah keserdaduan dan di ranah politik bisa-bisa tidaklah sama persis. Ketika seorang serdadu (mantan) masuk dunia politik, ia sebenarnya harus bekerja keras untuk menghayati ‘dunia kematian’ di ranah politik. Kematian berdarah-darah penuh luka tembak atau tusuk mungkin tidak ditemui di ranah politik. Jarang sekali, meski tetaplah ada. Ada beberapa kasus. Yang sering adalah akibat dari (serangkaian) pembunuhan karakter, jadilah: mati karakter. “Berhenti’ pada keutamaan kehormatan -yang dijunjung tinggi dalam ‘kelas’ serdadu, jelas tidak cukup lagi ketika ia mau ada di puncak kekuasaan (politik). Selain ‘keutamaan tahu batas’, ia masih ditambah lagi satu keutamaan: prudence. Apalagi di era Abad Informasi ini, politik akan lebih diwarnai oleh ‘politik skandal’, demikian menurut Manuel Castells bahkan ketika sosial media belum dikenal seperti sekarang ini. Maka ‘pembunuhan karakter’ bisa-bisa menjadi mainan sehari-hari.
Lihat jika dirunut ke belakang, bahkan sejak hari-hari pertama sik-serdadu dilantik jadi ‘panglima tertinggi’, pembunuhan karakter itu sudah mulai ‘dibingkai’. Bingkai monster-isasi. Mungkin saja ia dengan ‘penuh kehormatan’ memegang ‘perjanjian’ tertentu, tetapi sadarkah ia bahwa yang dihadapi adalah para machiavellis? Machiavelli pernah mengingatkan bahwa dalam ranah kuasa itu yang berhasil bisa-bisa yang dengan enteng-enteng saja mengingkari perjanjian. Bahkan sejak hari pertama ‘pihak sono’ sudah mulai ‘membenamkan’ segala yang mau dipegang oleh yang memegang kehormatan itu. Sik-serdadu ‘lupa’ bahwa yang dihadapi ini sudah terbukti selama sepuluh tahun sama sekali tidak paham soal kehormatan lagi.
Dalam alam raya keserdaduan, ketika komandan ingin mengambil keputusan terutama dalam perang (dan sebenarnya itu dilatih juga dalam keseharian), ia akan memanggil staf-stafnya untuk diminta laporan situasi terkini. Staf logistic bagaimana? Infanteri bagaimana? Dan banyak lagi. Dari situ ia kemudian mengambil keputusan. Dengan struktur komando ketat a la keserdaduan, kecil kemungkinan para staf akan memberikan informasi salah, atau bertentangan dengan kenyataan yang menjadi tanggung jawabnya. Bisa ‘ditembak di tempat’ jika semau-maunya, apalagi jika perang di depan hidung. Ngeri, cuk … Tetapi dalam politik kuasa bisa lain, apalagi jika faktanya ia ada dalam situasi ‘matahari kembar’. Lihat bagaimana bawahan yang ditunjuknya itu dengan tanpa beban lagi berani menipunya, bahkan di depan orang banyak. Bagaimana listrik? Siap, sudah menyala 93%, katanya lantang, meski dalam hati sangat mungkin sambil pecingas-pecingis. Jika itu rapat serdadu di garis depan medan perang, langsung ditembak orang semacam itu.
Maka menghadapi ‘mati sesungguhnya’, itu adalah hal yang akan dihadapi sendiri, tidak bisa diwakilkan pada siapapun. Tetapi ‘mati karakter’ jelas tidak akan dihadapinya sendiri, orang-orang sekitar akan sangat menentukan bagaimana ‘mati karakter’ ini akan mendekat atau menjauh. Satu-satunya ‘mati karakter’ menjadi urusan sendiri adalah ketika ia mbudeg, tidak mau mendengar, bahkan terhadap lingkar terdekatnya. Sudah tidak bisa dikandani, tidak bisa diberitahu lagi. Bagi ‘musuh-musuh politik’-nya, hal ini bisa menjadi ‘hal strategis’ untuk dieksploitasi. Perbanyak orang-orang sekitar, terutama untuk memberikan bermacam informasi yang efeknya tidak hanya salahnya informasi yang berujung kebijakan salah pula, garbage in garbage out, tetapi juga in-formatio itu juga akan ‘membesarkan kepala’ sik-panglima tertinggi. Machiavelli sebenarnya sudah mengingatkan bagaimana para penjilat ini mesti ‘dikelola’. Maka, para machiavellis-pun tentu paham apa yang bisa diperbuat oleh para penjilat ketika itu ada dalam orkestrasi ‘matahari lainnya’. Dengan latar belakang keserdaduan yang memegang teguh kehormatan, sayangnya dengan itu pula ia bisa ‘lebih mudah’ untuk dijerumuskan dalam mode bablasannya, katakanlah: megalomania. Dan begitu masuk dalam mode bablasan itu, bisa dipastikan keutamaan prudence-pun akan tertekan juga. *** (31-12-2025)




1838. Kekerasan 2021
02-01-2026
Judul tidak salah, dan memang bukan ‘kekerasan 1312’, tetapi 2021, Mengapa? Karena ‘panglima tertinggi’ salah sebut, bukan tahun baru 2026, tetapi 2021. Dengan mantapnya. Orang kebanyakan bisa saja melihat sebagai selip lidah, biasa-biasa, sama sekali tidak luar biasa. Tetapi bahkan selip lidah bisa berdampak macam-macam, lihat di Jepang, pejabat tidak bisa lagi berlindung di balik peristiwa selip lidah terhadap lontaran kata-kata yang menyakitkan sementara pihak. Ia akhirnya mengundurkan diri. Artinya, semakin tinggi jabatan (publik) yang namanya selip lidah itu semestinya sangat minimal, karena setiap kata yang keluar harusnya dipikir lebih dahulu. Itu bukan hanya pada dampak, tetapi terlebih karena tanggung jawabnya.
Tentu jika salah sebut: seharusnya 2026 tetapi disebut 2021, tidaklah akan mengakibatkan tuntutan pengunduruan diri dari jabatan. Bahkan jika itu di Jepang sono. Khalayak kebanyakan akan sangat bertoleransi terhadap kesalahan tersebut. Masalahnya kata tidak hanya soal ‘konteks’ tetapi juga ‘sejarah’. Termasuk dalam hal ini, ‘sejarah’ kesehatan sik-panglima tertinggi. Apakah salah sebut itu tanda sebuah penurunan kesehatan? Bagi yang pernah mengalami stroke misalnya, kemungkinan akan mendapat serangan ulang jelas lebih besar dari yang belum. Baik dari yang paling ringan atau sampai berat. Apalagi di usia tua. Terlebih jika terlalu capek dan marah-marah melulu, misalnya. Dan banyak jalan menuju capek buat sik-tua, termasuk juga banyak jalan untuk membuatnya terus marah-marah melulu. Selain tentu factor diri yang bisa saja tidak mudah dikandani, tidak mudah diberitahu atau diberi saran. Ndableg.
Sah-sah saja jika khalayak kebanyakan bertanya-tanya, ngapain sik-panglima tertinggi itu bolak-balik memantau penanganan bencana secara langsung, apakah bawahannya tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik? Bahkan soal baut jembatan (di)lepas-pun ada yang merasa perlu untuk ‘konperensi pers’ bahkan komplit dengan bumbu ‘sabotase’. Aèng-aèng saja. Bahkan kalau toh itu benar, mbok lihat gambar besar-nya, bencana dengan segala akibatnya itu. Tahan segala informasi ‘intelijen’ tingkat dewa itu sebagai catatan-catatan strategis sendiri. Hari-hari ini fokus saja pada segala upaya membantu korban, seperti yang dimaui sik-panglima tertinggi. Jangan malah membuat sik-panglima tertinggi merasa perlu datang jauh-jauh dan mencoba langsung jembatan yang dibuatnya, bikin capek saja …
Maka semakin nampak saja ada beberapa hal perlu dicermati, bagaimana bikin capek dan bikin marah-marah melulu itu tidaklah di ruang kosong, hal tersebut ada dalam ranah ‘perebutan kuasa’. Bagaimana sik-tua itu dibuat ‘cepat sakit’. Teori konspirasi? Mungkin saja, mungkin tidak, maka ada baiknya kita kembali ‘ke sesuatu itu lagi’ secara lebih teliti. Jadi tetaplah terbuka untuk iya atau tidak. Hal lain seperti sudah berlangsung sejak hari pertama menjabat: monsterisasi. Banyak upaya yang ditujukan supaya khalayak kebanyakan mau menunjuk bahwa sik-tua itu adalah monster, sekali lagi: sejak hari pertama menjabat. Lihat hari-hari ini, bagaimana yang kritis terhadap penanganan bencana itu mengalami terror, yang bahkan bentuk terornya sungguh telanjang. Tidak hanya satu yang diteror, tetapi dua-tiga-empat orang, dan seterusnya. Nyaris kita tidak pernah mendengar adanya terror terhadap seseorang ketika bencana datang. Atau dalam rentang kebencanaan. Nyaris tidak ada. Tetapi nyatanya itu ada, dan di depan hidung! Aèng-aèng saja.
Maka ‘selip lidah 2021’ di atas bisa-bisa akan memperbesar potensi kekerasan, kuda-kuda yang sudah disiapkan satu-per-satu mulai dipasang untuk masuk ranah ‘perebutan kuasa’. Tidak penting apakah kata 2021 itu sekedar selip lidah atau penampakan dari upaya panjang bikin capek dan bikin marah melulu, tetap saja akan ada yang meyakini bahwa memang ‘waktunya sudah dekat’. Benar SBY beberapa waktu lalu memperingatkan soal ‘matahari kembar’, dan kita semakin merasakan bahwa itu pertaruhannya sangat-sangat besar. Dan siapa korban utamanya? Rakyat kebanyakan, terutama yang hidup pas-pas-an. Di tengah-tengah segala ketidakpastian, akibatnya bisa-bisa akan lebih besar lagi. *** (02-01-2026)
1839. 15 Bulan Kehamilan Monster?
03-01-2026
Berapa bulan lama kehamilan sehingga monster akan dilahirkan? Lama kehamilan kucing sekitar 65 hari, manusia 9 bulan lebih beberapa hari, gajah antara 20-24 bulan, monster? Adakah yang sedang menunggu-nunggu kelahiran seorang monster dengan penuh harap? Monster yang akan dilahirkan itu diharapkan mau mendonorkan semua organ-organnya demi langgengnya rejim terdahulu? Artinya, monster dilahirkan untuk disembelih beramai-ramai sebagai ‘kambing hitam’, mau atau tidak mau: harus jadi ‘kambing hitam’. (Lihat catatan kaki di bawah: ‘Nasib Sik-Monster [1]) Ramai-ramai disembelih setelah mau ‘menertibkan’ semua saja yang merecoki (kepentingan) rejim terdahulu.
Apa kepentingan utama rejim terdahulu? Jika kita membayangkan asal kata republik, res-publika, maka kepentingan utama rejim terdahulu adalah mempertahankan res-privata yang semakin mendekati ‘kesempurnaan’-nya. Menjadi urusan privat-privat dalam arti sik-‘raja’ dan para ‘pangeran’-nya. Privat-privat yang sudah dengan ‘susah payah’ membangun system perampasan kekayaan republik yang sudah mendekati ‘sempurna’. Mengapa ‘sempurna’? Karena hasil-hasil perampasan itu tidak hanya soal ‘Panama papers’ saja, tetapi semakin menemukan jalan ‘pencucian domestik’-nya. Bahkan seakan itu tidak hanya soal ‘pencucian uang haram’ tetapi juga bisa-bisa merupakan bagian dari ‘pencucian dosa’ terhadap republik yang telah ditelikungnya habis-habisan. Para ‘privata’ seperti dimaksud di atas, bisa-bisa sudah merasa ikut meningkatkan ‘pertumbuhan ekonomi’ republik, atau ikut menyediakan lapangan pekerjaan bagi khalayak kebanyakan. Logika trickle-down effect seakan telah menjadi salah satu ‘pencucian dosa’ ini. Dan siapa mau kehilangan segala ‘kenikmatan paripurna’ ini? Kenikmatan akan uang-uang-uang. Tak mengherankan jika kemudian sik-‘raja’ dinobatkan sebagai pemimpin paling korup se-planet pada rentang waktu nominasi tertentu. Nomer dua paling korup sedunia! Tak mengherankan pula kedaulatanpun kemudian dengan tanpa beban lagi digadaikan habis-habisan. Maka jangan heran ketika segala kenikmatan itu akan dipertahankan dengan modus at all cost. *** (03-01-2026)
[1] Salam dari Sang Penguasa: Nasib Sik-Monster
Ketika sang pangeran telah menguasai Rogmana dan merasa perlu untuk menenangkan dan membuat Rogmana patuh kepada pemerintahannya, ia menunjuk Remirro de Orco, seorang yang kejam, cakap dan diberinya segala kepercayaan dan wewenang. Dalam waktu yang singkat, Remirro telah berhasil memulihkan tata tertib dan persatuan dan mendapatkan pujian besar.
Kemudian sang pangeran mengambil keputusan bahwa wewenang yang berlebihan ini tidak diperlukan lagi, karena bisa tumbuh dan tak dapat dikendalikan lagi. Karena itu ia mendirikan di tengah propinsi sebuah pengadilan sipil, yang dipimpin oleh seorang ketua yang sangat terkenal. Setiap kota mempunyai perwakilannya di pengadilan tersebut. Dengan menyadari bahwa kekejaman dari masa lalu telah banyak menimbulkan kebencian padanya, sang pangeran bertekad untuk membuktikan bahwa kekejaman yang ditimpakan, bukanlah merupakan tindakannya, tetapi dilakukan oleh sifat kejam para menterinya.
Cesare menunggu kesempatan baik ini. Kemudian, pada suatu pagi, tubuh Remirro ditemukan terpotong dua di lapangan Cesena bersama sepotong kayu dan sebilah pisau berdarah di samping tubuhnya. ***
*) Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, Penerbit Gramedia, 1987, hlm. 29-30