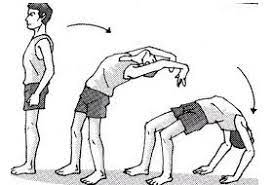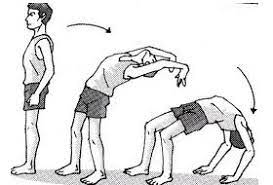1850. "Operasi Teheran"
13-01-2026
Sebuah operasi digelar untuk mendongkel Salvador Allende (Cile) di awal decade 1970-an, di puncak Perang Dingin, di awal-awal paradigma neoliberalisme mau diuji-coba oleh rombongan Chicago Boys, dan nama operasinya adalah Operasi Djakarta. Apakah ‘Operasi Teheran’ akan menjadi kata sandi sebuah operasi untuk menjatuhkan rejim yang demen ‘anti-asing’? Dari pemberitaan kita bisa melihat bertahun-tahun pemimpin Iran selalu lekat dengan retorika anti Amerika, anti-Israel. Tentu silahkan saja dan mungkin saja punya alasan kuatnya, masalahnya apakah rakyat akan kenyang begitu saja dengan ajakan heroic untuk melawan osang-asing itu? Apapun retorika yang dibangunnya?
Demen dengan retorika anti-osang-asing tentu adalah sebuah pilihan, silahkan saja …. cuk, tetapi lupa untuk mensejahterakan rakyatnya tentu bukan pilihan, terutama bagi khalayak kebanyakan. Itu adalah kewajiban, sekali lagi, bukan pilihan. Bayangkan, masalah makan gratis di sekolah dan (versus) hari libur sekolah-pun tidak bisa dikelola dengan ‘bermartabat’, pating pecothot apa-apa yang keluar dari petingginya, maunya sih memberikan penjelasan, hasilnya? Prèk. Asal mangap asal njeplak itu akankah menjadi ‘bermartabat’ ketika anti osang-asing ditabuh genderangnya? Yang nggak-lah … Lihat, begitu rapuh bangunan argumentasinya, semau-maunya, seakan menggambarkan bagaimana argumentasi dalam mengelola republik secara umum yang sering menampakkan begitu rapuh adanya. Di tengah segala ketidak-pastian, kerapuhan pasti bukanlah pilihan. Segala kerapuhan, fragilitas yang ‘terbangun’ selama bertahun ini, sungguh semakin ‘menggelisahkan’ terlebih ketika ketidak-pastian global itu semakin menampakkan sisi brutalnya. Brutal adalah serapan bahasa asing yang dari asal katanya dekat dengan pengertian ‘perilaku kebinatangan’.
Maka menghadapi tidak hanya ketidak-pastian, tetapi juga brutalitas, satu-satunya pilihan trategis adalah memaksimal segala kapasitas manusia, terutama kapasitas berpikirnya. Berpikir yang sungguh membedakan manusia dengan dunia binatang secara mendasar. Berpikir termasuk di sini dalam membedah ancaman brutalnya kekuatan kekerasan ataupun brutalnya kekuatan uang. Masa lalu memberikan pelajaran bagaimana keberpikiran itu bisa secara telak dipinggirkan, itu terutama adalah karena eksploitasi hasrat yang sudah sampai pada tahap kegilaannya. Kegilaan hasrat akan uang, dan atau kegilaan akan hasrat terhadap hal-hal besar. Kegilaan anti osang-asing itu pada dasarnya adalah salah satu wujud dari kegilaan hasrat akan hal-hal besar, akhirnya menjadi ‘kejahatan logika’ dalam memandang yang serba asing. Tentu kewaspadaan terhadap kepentingan asing perlu terus ada dan dijaga, bahkan perlu itu selalu diperhitungkan terkait dengan bagaimana kepentingan nasional terus diupayakan, tetapi menjadi kegilaan dalam retorika? Kapan itu menjadi sebuah kegilaan? Ketika itu telah ‘membunuh’ akal sehat, telah menekan ke-prudence-an dalam melihat dan mengelola apa-apa yang menjadi tanggung jawab utama: mensejahterakan rakyatnya. Atau menjadi malas berpikir untuk menentukan hal-hal mendasar terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Energi atau focus banyak digerogoti oleh imajinasi terhadap yang ada di jauh sana, osang-asing. Akhirnya isi tindakan justru banyak menghambur-hamburkan bermacam sumberdaya, apapun itu. Dihambur-hamburkan dengan tanpa beban. Lupa bahwa masalah dalam negeri-pun sudah akan menguras banyak imajinasi, banyak energi. Godaan ‘jalan gampang’ akhirnya menjadi begitu mudah untuk dirangkul. Kritik kemudian dianggap ‘jahat’. Lingkaran setan megalomania itu semakin membayang saja.
Jika muncul kata yang kemudian menjadi mudah diserap khalayak seperti ‘akal sehat’, ‘salam akal waras’, ‘salam cerdas’, atau bahkan ‘dungu’ atau ‘plonga-plongo’ itu sedikit banyak memberikan gambaran memang ada situasi dimana keberpikiran itu memang bertahun telah dipinggirkan. Terutama dalam pengelolaan negara. Istilah-istilah yang mudah diserap karena ternyata ketidak-berpikiran berjalan seiring dengan ketidak-adilan yang semakin menguat. Bertahun terakhir adalah bukti telanjang bagaimana ketidak-berpikiran telah membuat rapuh hidup bersama. Dalam semua aspeknya. Kerapuhan yang akan membuat daya tahan dalam menghadapi kebrutalan ketidak-pastian global akan menjadi begitu tipisnya. Akankah republik akan menjadi Iran selanjutnya? Jika tidak mau (menjadi seperti Iran hari-hari ini), hentikan itu retorika anti osang-asing yang justru malah -sadar atau tidak, jadi tirai tebal dari ketidak-mampuan dalam mengelola negara secara prudence. Aèng-aèng saja … *** (13-01-2026)
1851. Problem Sumbu Pendek
14-01-2026
Dalam satu komunitas, kadang belitan masalah muncul lebih berasal dari pemimpin mereka. Bahkan dalam komunitas dengan power distance (Hofstede) rendah seperti Inggris misalnya, bertahun terakhir nampak bagaimana kepemimpinan ‘yang lemah’ mewarnai banyak kemunduran atau kedodoran dalam berbagai aspeknya. Apalagi dalam komunitas dengan power distance tinggi dimana khalayak kebanyakan cenderung tidak mempermasalahkan atau tidak rèsèh terhadap perbedaan atau bahkan njomplangnya distribusi kuasa. Ambyarnya kualitas kepemimpinan bisa-bisa belitan masalah khalayak kebanyakan jadi tak kunjung terurai, bahkan semakin erat mencengkeram.
Bertahun terakhir ada pelajaran berharga bagaimana problem plonga-plongo sebuah kepemimpinan dapat begitu mempengaruhi hidup bersama. Mengapa ini bisa menjadi masalah? Meski banyak perkembangan setelah Freud, tetapi bayangkan jika semua orang berjalan sesuai dengan ‘kondisi asali’-nya, lebih banyak didorong oleh ‘ketidak sadaran’-nya, atau katakanlah id-nya. Sementara pemimpin tidak kunjung menunjukkan kemampuan nalarnya dengan baik, maka edaran bahan untuk mekanisme mirror neuron system-pun menjadi semakin sedikit terkait peran nalar dalam hidup bersama. Terlebih ketika dalam hidup bersama lembaga penelitian diobok-obok atau dikerdilkan, termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan, terutama perguruan tingginya. Apalagi ketika pemimpin dengan sengaja membangun rejim dengan salah satu pilar penting adalah dengan eksploitasi hasrat (gelap) akan uang. Siapa saja boleh korupsi misalnya, asal mau mendukung rejim. Bukan tanah yang dibagi-bagi kepada para pangeran atau tuan tanah seperti jaman feodal, tetapi lapak-lapak basah dalam hidup berbangsa-bernegara. Akhirnya res-publika itupun menjadi res-hasrat dengan meminggirkan secara telak nalar. Tidak hanya terpinggirkan, tetapi nalar perlahan menjadi ‘musuh bersama’. Diolok-olok tanpa henti. Maka tak mengherankan ketika ada yang menggunakan nalar secara terus menerus tanpa henti, tanpa rasa takut seperti dalam isu ijazah palsu misalnya, meraka tergagap-gagap dan semakin nampak kedodoran. Andalan mereka tetap saja sama, menolak nalar dengan selalu saja berharap pada efek bandwagon. Jika ada yang ‘banyak’ bilang asli maka itulah yang benar. Lupa bahwa nalar-pun bisa melahirkan ‘efek bandwagon’ meski memang perlu waktu lebih lama.
Bagaimana dengan problem sumbu pendek? Percobaan Milgram di sekitar 1960-an bisa dilihat juga bagaimana jika sebuah sumbu ‘dipendekkan’. Terutama dengan hadirnya sik-pengawas. Para peserta percobaan Milgram itu tentu ada yang berkategori ‘plonga-plongo’, tetapi sebagian besarnya tidak, bahkan ada yang dari kalangan cerdik-pandai. Bahkan pemuka agama juga ada. Tetapi sebagian besarnya -menurut hasil penelitian, ternyata mampu dengan tanpa beban memberikan ‘sengatan listrik’ dengan voltase tertinggi kepada ‘murid’ yang salah jawab. Dua hal yang memungkinkan itu terjadi, tentu pertama-tama adalah adanya sik-pengawas, kedua: imajinasi tentang hal-hal besar yang menjadi tujuan penelitian, yaitu mencari jalan benar dalam mendidik siswa.
Dalam Fenomenologi, dikenal adanya sikap alamiah dan sikap fenomenologis. Ada langkah epoche atau ‘memberi tanda kurung’ dulu (menunda) dalam sikap fenomenologis. Sebagian besar hidup kita akan kita jalani dengan ‘sikap alamiah’, akan repot jika sedikit-sedikit kita ‘tunda’ lebih dulu, dan melihat sesuatu hal sebagai ‘pemula’ dan kemudian menelisik dari berbagai aspek, sudut, profil sesuatu itu untuk membedah apa yang menjadi esensinya. Repot, maka sebagian besar hidup memang kita jalani dengan modus taken for granted. Tetapi apakah dalam beberapa hal atau peristiwa kita akan mengambil sikap taken for granted juga? Pemimpin, terlebih sudah kita ‘biayai’ dengan pajak-pajak kita, maka diharapkan ia tidak mudah memutuskan dengan modus taken for granted saja. “Sumbu” taken for granted itu perlu diperpanjang sehingga mempunyai banyak waktu dan kesempatan dalam hal timbang-menimbang.
Masalahnya -kembali pada percobaan Milgram di atas, bagaimana jika maunya ‘menunda’ lebih dulu bermacam laporan masuk dan ingin melihat secara langsung penanganan bencana misalnya, dan ingin tahu soal apakah listrik sudah menyala, langsung saja ‘digertak’ oleh salah satu ‘pengawas’: 93% persen sudah menyala! Bayangkan jika ‘hal-hal besar’ tentang penanganan bencana sudah menguasai imajinasi, mungkin saja langsung percaya! Bayangkan pula itu terjadi untuk hal-hal lain dimana dalam keseharian ia selalu saja dilekati oleh banyaaak sik-pengawas yang selalu beredar di sekitarnya? Apalagi tidak hanya ‘dikombinasi’ dengan imajinasi tentang ‘hal-hal besar’ tetapi juga ditambah ada kecenderungan dalam diri terkait ‘pendeknya sumbu’? Apakah kemudian ia akan ‘menyetrum’ para pengkritiknya? Dikritik lagi, voltase ditingkatkan. Hingga suatu saat sampai pada voltase tertinggi? Padahal kritik salah satunya adalah juga dorongan bagi seorang pemimpin untuk mau dan mampu ‘menunda’ lebih dahulu sehingga mau melihat (ulang) banyak halnya dari bermacam aspek, sudut, profil, atau lainnya secara prudence. *** (14-01-2026)


1852. UGM Menggugat!
15-01-2026
UGM Menggugat! Demikian judul satu pamphlet-edaran dari petinggi UGM, tak kalah dengan tulisan si-Bung: Indonesia Menggugat. Rakyat terjajah sedang menggugat penjajahan saat itu, demikian kira-kira imajinasi si-Bung. Tak jauh berbeda nuansa UGM Menggugat, ketika penguasa berperilaku layaknya penjajah saja. Terutama ketika penguasa justru tanpa henti membuat bodoh rakyat. Membuat rakyat kesulitan keluar dari kesulitan sehari-hari. Ketika kekayaan alam dirampok dengan ugal-ugalan. Ketika korupsi meraja-lela di tengah-tengah rakyat kesulitan mempertahankan hidup. Ketika program-program pemerintah diputuskan secara tidak hati-hati, apalagi dalam pelaksanaannya. UGM Menggugat begitu prihatin bagaimana sumber daya yang serba terbatas ini dikelola secara ugal-ugalan, sama sekali tidak memperhatikan dampak jangka panjangnya. Bahkan dampak jangka pendekpun luput dari perhitungan secara prudence.
Tetapi UGM Menggugat lebih menyoroti dunia pendidikan, terlebih dunia perguruan tinggi. Terutama para petingginya, pengelola dari hari ke hari sebuah perguruan tinggi. Diingatkan bagaimana peran pendidikan dalam kontribusi besarnya di awal-awal perjuangan republik sehingga semakin mampu menggapai kemerdekaannya. Dingatkan bahwa kehormatan dan integritas itu melampai capaian akademik apapun, sebab kehormatan dan integritas semestinya menjadi bahan bakar utama dalam pengembangan kemampuan akademik. Kehormatan dan integritas pengelola perguruan tinggi, diingatkan dalam UGM Menggugat, bisa menjadi pintu masuk terhadap segala ambruknya kehormatan dan integritas akademik. Jika pimpinan sudah kehilangan kehormatan dan integritas, apalagi jika itu didorong oleh masalah uang, maka hancurnya bangunan kekuatan pengetahuan akan segera membayang lekat.
Terhadap munculnya kasus-kasus ijazah palsu, UGM Menggugat menegaskan bahwa kasus seperti itu bukanlah kasus kecil, tetapi hal besar juga mendasar. Jangan sekali-kali mentelorir kasus ijazah palsu, demikian tegas UGM Menggugat yang ditandatangani oleh para petinggi UGM[1] itu. Bahkan terhadap semua yang terlibat dalam kasus ijazah palsu, UGM Menggugat menegaskan bahwa mereka tidak hanya pengkhianat akademik, tetapi juga pengkhianat kehormatan dan integritas. Bahkan juga pengkhianat republik. Sebagai pengkhianat mereka layak diarak keliling kampus dengan punggung diberi tulisan: pengkhianat! Ditonton oleh seluruh civitas akademika. Para pembayar pajak budiman tentu boleh ikut menonton, sambil lempar koin-koin atau lembar uang di depan para pengkhianat itu. *** (15-01-2026)
[1] UGM di sini tentu bukan Universitas Gajah Mada, tetapi Universitas Gajah M ---- (silahkan diteruskan sendiri-sendiri)